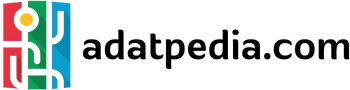Calistung Adalah Kunci Penerus Masyarakat Adat
Adatpedia – Masyarakat adat Wana Posangke di Sulawesi Tengah yang jauh terisolasi dari akses pendidikan, penting menjadi pintar agar meneruskan pola pengelolaan sumber daya alam lestari.
Bertahun lalu, Sera masih berusia 10 tahun. Sejak berumur 8 tahun dia tinggal di pusat desa di Taronggo. Desa itu adalah satu-satunya desa terdekat yang menyediakan sekolah umum. Jaraknya mungkin hanya sekitar 10 kilometer dari Lipu Salisarao. Tapi pusat desa hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama hampir seharian melewati perbukitan dan menyeberangi sungai.
Lipu, dalam terminologi orang Wana Posangke di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, merupakan satu unit perkampungan yang terletak jauh di dalam hutan. Sera adalah keturunan suku Wana.
“Saya ingin kembali ke Lipu,” ungkap Sera kala itu. Ia ingin kembali menikmati belajar di Sekolah Lipu, sebuah sekolah non formal.
Guru Sekolah Lipu, Ma’in mengatakan sekolah Lipu sudah dimulai sejak Sera berusia 6 tahun. Dia menggunakan sebuah papan untuk menulis beberapa kata sederhana yang dapat dieja.
“Belajar tak bisa terus di ruangan. Kami pakai metode sambil bermain. Kadang juga belajar di luar ruangan. Waktunyapun disesuaikan dengan kesempatan. Kadang Sekolah Lipu libur jika anak-anak turut ke ladang bersama orangtuanya,” papar Ma’in.
Di sini, lanjutnya, tak ada mata pelajaran. Proses belajar akan disesuaikan dengan keadaan. Dengan kondisi itu, guru-guru Sekolah Lipu tentunya harus berbekal pengetahuan yang luas.
Sekolah Lipu adalah alternatif mendapatkan pengetahuan, membaca dan menghitung. Konsepnya, semua tempat adalah ruang belajar, semua orang adalah guru dan semua pengalaman adalah materi pelajaran.
Hal ini tentu membuat minat belajar semakin meningkat. Tidak sedikit orang tua yang bersedia menjadi murid Sekolah Lipu. Setidaknya sudah ada 7 Sekolah Lipu di wilayah adat Wana Posangke.
“Dengan membaca, mereka berharap agar tidak akan dibohongi jika menjual hasil hutan bukan kayu. Termasuk memperjuangkan hak-haknya sebagai masyarakat adat,” kata Ma’in.
Dalam belajar, kata Ma’in, kerap pula materi tentang sosial budaya orang Wana menjadi topik bahasan. Sebagai orang Wana, tentunya Ma’in tak mau ciri khusus mereka lenyap. Dia ikut menuturkan berbagai tradisi dan kebiasaan suku Wana pada anak-anak, termasuk tentang pola penggunaan lahan.
Alvard M dalam catatannya bertajuk The potential for sustainable harvests by traditional Wana hunters in Morowali Nature Reserve, Central Sulawesi, Indonesia dan The impact of traditional subsistence hunting and trapping on prey populations: Data from the Wana of upland Central Sulawesi, Indonesia, tahun 2000 sudah menyebut penggunaan lahan oleh orang Wana tidak luas, tidak ekspansif dan juga tidak eksploitatif.
Catatan itu mengungkap, satu rumah tangga Wana menggunakan lahan yang tak lebih dari sehektare untuk pertanian. Di dalamnya sudah mencakup lahan untuk tanaman pangan utama dan tanaman pangan sekunder, termasuk rotasi perladangan dengan siklus terjaga antara 1 – 5 tahun.
“Kami orang Wana, akan datang kembali ke bekas ladang setelah ditinggalkan. Jadi tidak ada istilahnya ladang berpindah seperti istilah orang di kota. Kami yakin tanah bekas ladang itu akan kembali subur untuk menumbuhkan padi,” papar Ma’in.
Orang Wana, lanjut Ma’in, mengenal pengelompokan ladang. Tou, yakni ladang padi untuk padi yang usianya lima bulan. Bonde, yakni ladang padi yang usianya tiga bulan. Tak ada mekanisasi apalagi pupuk, semua serba tardisional.
Tapi, lanjutnya, dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun itu banyak terjadi perubahan. Kadang ladang yang ditinggalkan sudah menjadi kebun sawit atau tempat operasi tambang.
“Itu yang menjadi konflik. Karenanya generasi Sera akan menjadi penerus budaya orang Wana. Mereka penting menjadi orang-orang pintar. Membaca, menulis dan berhitung adalah kunci,” tandasnya. (Syafrizaldi Jpang)